RITUAL DAN KEGIATAN PERTANIAN LAHAN KERING DI TUNBABA DI PULAU TIMOR
Masyarakat ATONI PAH METO (orang gunung) di Tunbaba, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagian besar adalah petani lahan kering dengan sistem lahan berpindah dan tebas bakar (Foni, 2002, p. 109). Siklus pertanian mereka terdiri atas 18 etape (ritual atau upacara), yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Masyarakat Timor, khususnya Tunbaba, menghayati konsep hidup menyatu dengan leluhur mereka di setiap ruang kehidupan mereka, maka ‚Äúdunia orang hidup berimpit dengan dunia arwah‚ÄĚ, sehingga ritual adat merupakan bagian dari gaya kehidupan mereka sehari-hari (Purbadi, 2010).
Perlu diketahui, cara berkebun orang Timor di Tunbaba menggunakan ‚Äúpola tumpangsari‚ÄĚ seperti yang dilakukan oleh para petani di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dicermati, lahan yang mereka gunakan dan musim hujan yang pendek sama pada kedua daerah tersebut. Lahan di pulau Timor adalah ‚Äúbatu bertanah‚ÄĚ, bukan ‚Äútanah berbatu‚ÄĚ, yang lebih dominan batunya daripada tanahnya yang subur. Orang Tunbaba biasa menanam berbagai tanaman pada satu lahan yang sama dan bersama-sama, namun yang selalu disebut dalam doa ritual hanya padi dan jagung. Artinya, padi dan jagung menduduki tempat istimewa dalam budaya orang Tunbaba. Kebun mereka biasanya ditanami padi, jagung, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sorgum, pisang dan berbagai tanaman lain karena memiliki waktu tanam dan panen yang berbeda-beda. Pola itu merupakan salah satu unsur ketahanan pangan di Tunbaba (Foni, 2002).
Masyarakat petani lahan kering di Tunbaba memiliki siklus pertanian disertai dengan ritual-ritual khusus pada tahapan-tahapan pertanian. Setiap ritual, memiliki tendensi menjalin dan memelihara hubungan atau komunikasi harmonis antara manusia (atoni pah meto) dengan kekuatan di luar dirinya, yang lebih suci, lebih besar dan lebih tinggi dari dirinya(Foni, 2002, p. 109). Orang Tunbaba memiliki konsep kehidupan ideal yang khas. Konsep kehidupan ideal menurut orang Tunbaba pada umumnya sama dengan konsep yang ditemukan di desa Kaenbaun, yaitu: ‚ÄúAtone kuan ‚ÄúKuun Kaenbaun, Take nael Naijuf‚ÄĚ ina monena mataos ‚Äď in pauk pina ma ai pina; halon ‚Äď manonbon ma natnanbon natuin uis neno afinit ma aneset ‚Äď amoet ma apakaet ‚Äď apinat ma aklahat; bei na‚Äôi-uis kinama-tuakin; pah-tasi ma nifu‚ÄĚ(Purbadi, 2010). Ungkapan tersebut mengandung konsep bahwa kehidupan ideal sangat ditentukan oleh interaksi empat unsur utama, yaitu (1) Tuhan (Uis Neno), (2) Nenek-moyang (bei nai), (3) manusia (atoni),¬†dan (4) alam semesta (universe)(Purbadi, 2010, p. 618).Oleh karenanya, ritual-ritualapapun selalu tertuju pada maksud pencapaian hidup ideal sesuai dengan konsep yang mereka hayati.
Ritual pertanian selalu dipimpin oleh orang atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas adat urusan tanah yang disebut ‚Äúmaveva‚ÄĚ. Upacara adat masyarakat Timor biasanya menggunakan korban hewan (babi atau ayam) dan diakhiri dengan makan secara adat (disebut¬†sea kete) disertai nasi dan sopi (arak lokal), yang artinya mengambil bagian dalam persembahan kepada nenek-moyang. Ritual di rumah adat (ume kanaf) selalu diawali dengan doa di depan tiang suci (haumonef)¬†yaitu tiang kayu cabang tiga yang melambangkan¬†Usi Neno Mnanu¬†(Tuhan Allah yang Tinggi, jauh tak terjangkau),¬†Usi Neno Pala¬†(Tuhan Allah yang pendek, dekat dan terjangkau), dan¬†B‚Äôei Nai¬†(Arwah leluhur) (Foni, 2002; Purbadi, 2010).
 
Haumonefumesuku (rumah adat suku) Basan di desa Kaenbaun (Purbadi, 2010, p. 274)
Dalam ritual adat pertanianselalu diawali dengan doa kepada pah¬†maisokan(roh-roh setempat) agar mereka dan anak-anaknya turut ambil bagian dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. (Sea teke merupakan puncak acara dalam ritual adat masyarakat Timor, yaitu makan bersama meriah antara warga yang masih hidup (anak cucu) dengan nenek-moyang leluhur mereka (Foni, 2002; Purbadi, 2010).Upacara makan seperti itu melambangkan keakraban, keutuhan dan persaudaraan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan arwah-arwah menurut agama lokal atau kepercayaan adat yang mereka hayati. Setiap upacara adat selalu diawali dengan acara berkumpul bersama disebut ‚Äúnekaf mese ansaof mese‚ÄĚ yang bertujuan menyatukan hati dan jiwa sesama manusia (atoni) untuk menghadap leluhur (Purbadi, 2010).
 
Para tetua adat Timor di desa Kaenbaun sedang membaca pesan nenek-moyang pada organ dalam (hati) hewan korban dalam suatu ritual adat (Purbadi, 2010).
Dalam ritual adat apapun di wilayah Tunbaba selalu digunakan lilin menyala, sirih-pinang, hewan korban (ayam, kambing, babi, atau sapi), dan sopi (arak lokal), yang diminum oleh pemimpin upacara adat dan seluruh peserta upacara adat (Purbadi, 2010). Pada tengah upacara selalu ada pembacaan pesan (tae lilo) melalui organ tubuh dalam hewan korban. Jika pesan positif, maka ritual dilanjutkan dengan makan bersama (sae teke, tbukae tabua)(Foni, 2002; Purbadi, 2010). Jika pesan negatif, maka maveva akan mencari penyebabnya dan dilakukan upacara adat ulang (ta’tetun lilo) dengan perlengkapan hewan korban sesuai permintaan nenek-moyang, maka upaya ini merupakan usaha memperbaiki komunikasi dengan leluhur sampai memperoleh ijin dari mereka (Foni, 2002).
RITUAL-RITUALPERTANIAN LAHAN KERING DI TUNBABA
Dari penelitian yang dilakukan oleh Wilhelmus Foni (2002) diketahui bahwa terdapat 18 tahapan atau etape ritualdalam tradisi pertanian di wilayah Tunbaba yaitu berupa ritual-ritual yang dilaksanakaan sesuai dengan tahapan kegiatan pertanian. Ritual-ritual tersebut masih ada dan berlangsung secara tradisi turun-temurun. Delapan belas ritualyang ditemukan dapat dijelaskan dalam paparan berikut ini:
1. Ritual membuka lahan (Tafek Nono Hau Ana).
Ritual Tafek Nono Hau Ana dilakukan pada pembukaan lahan pertanian yang baru, biasanya dilaksanakan pada bulan Juli. Lahan tersebut dikerjakan kembali setelah ditinggalkan 3-5 tahun dan dianggap telah subur kembali. Tafek Nono Hau Ana adalah kegiatan memotong tanaman belukar menjalar, semak-semak dan pohon-pohon kecil untuk persiapan lahan perkebunan. Pada pohon-pohon besar dipangkas ranting-ranting yang diperkirakan menghalangi sinar matahari ke lahan perkebunan.
Ritual dilakukan di lahan ‚ÄúTobe‚ÄĚ (tuan tanah, suku pemimpin desa), di tempat tertentu yang disebut ‚Äúbale toko‚ÄĚ atau ‚Äútoko mnasi‚ÄĚ (tempat tua), yang sudah sejak lama dijadikan tempat upacara. Warga yang akan menggarap kebun berkumpul di tempat tua ini dan mendapat penjelasan serta arahan dari¬†tobe¬†(pemimpin kebun). Tobe juga mengarahkan tentang persiapan persembahan (hewan persembahan), permohonan ijin kepada nenek-moyang dan tuan tanah (najia tuaf), agar kegiatan berkebun lancar dan sukses.
Doa di bale toko dilakukan pada mesbah yang didirikan di dekat batang kayu besar (hau nasib atau hau matanik) sebagai istana para nenek-moyang suku-suku yang berhimpun di desa. Hal yang lazim bahwa di desa-desa di Timor terdapat beberapa suku yang berhimpun dan bersatu untuk hidup bersama sepanjang hayat, seperti terjadi di desa Kaenbaun ada suku Basan, Timo, Taus dan Foni serta suku Nel, Kaba, Salu dan Sait (Purbadi, 2010). Doa di tempat suci ini dalam tradisi masyarakat Timor selalu memadukan dua tradisi, yaitu tradisi Katolik dan kepercayaan setempat, sebab setiap upacara adat selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib Kristus (Foni, 2002; Purbadi, 2010).
Sebelum dilakukan upacara adat di bale toko, setiap keluarga petani yang akan mengikuti upacara¬†Tafek Nono Hau Anatelah¬†melakukan doa (ta‚Äôsine ume) di rumah masing-masing, di dekat tiang suci (ni ainaf) dan batu suci (fatu leu) rumah mereka. Doa mereka dilakukan di ‚Äúbatu suci‚ÄĚ (fatu leu) keluarga yang lazim ada di setiap rumah orang Tunbaba seperti di desa Kaenbaun (Purbadi, 2010). Pada doa keluarga ini, mereka mengundang semua nenek-moyang masing-masing untuk hadir dalam ritual¬†Tafek Nono Hau Ana¬†yang akan diadakan, termasuk semua kegiatan-kegiatan perkebunan yang diadakan di kebun (lele).
Selanjutnya, doa juga dilaksanakan di rumah suku (ume kanafdan ume mnasi) masing-masing suku, maka keluarga-keluarga yang terhimpun dalam suku tersebut hadir seluruhnya untuk berdoa bersama. Dengan demikian, terlihat bahwa ritual pertanian melibatkan semua pihak dan diawali dari rumah para petani, khususnya ruang doa mereka. Pola kegiatan ritual tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian atau perkebunan di kalangan masyarakat Timor adalah perbuatan suci dalam kerjasama dengan nenek-moyang (be’I nai) dan roh-roh setempat (maisokan) serta mendapat restu dari Tuhan Allah yang maha Tinggi (Usi Neno).
Doa mengelilingi batu suci (faut leu) dan tiang suci (ni ainaf) di rumah adat suku (umebubu) Taus di desa Kaenbaun (Purbadi, 2010, p. 288)
2. Ritual membakar tebasan (Tait Nuta ma Nopo)
Upacara ini biasanya dilaksanakan pada bulan September, pada saat hasil penebasan hutan dan kebun mengering. Pola upacaranya sama, namun dengan ujub doa yang berbeda, sesuai kepentingannya. Upacara ini ditandai dengan kegiatan membakar tebangan di kebun yang sudah dikerjakan pada tahap sebelumnya. Tait Nuta ma Nopo mengandung pengertian persiapan pembakaran kebun dengan menggunakan sebatang bambu. Sebelum membakar kebun, para pekerja kebun berkumpul dan berdoa bersama di bale toko yang digunakan juga untuk upacara Tafek Nono Hau Ana. Doa ditujukan pada permohonan restu nenek-moyang, roh-roh setempat dan Tuhan agar proses pembakaran kebun berlangsung aman dan lancar, dan tidak membakar area di luar kebun yang dikerjakan. Jika semak dan ranting yang dibakar habis terbakar, maka dianggap sebagai isyarat bahwa panen akan berhasil dengan melimpah. Pada waktu selesai pembakaran itulah, para pekerja bergembira ria dan melakukan aktivitas saling menyiram (maoip) sebagai wujud kebahagiaan (Foni, 2002). Mereka yang bekerja di ladang akan pulang ke rumah dengan keadaan gembira dan basah kuyup.
3. Ritual mendinginkan lahan (Tsifo Nopo)
Tsifo Nopo adalah upacara mendinginkan lahan dan menyejukkan semua peralatan yang digunakan pada saat membakar lahan(Foni, 2002). Upacara ini dilakukan esok hari setelah upacara Tait Nuta ma Nopo selesai dilaksanakan. Ritual atau upacara juga dilakukan di bale toko yang sama dan dihadiri para pekerja kebun dan keluarganya. Doa intinya adalah mohon kelancaran dan sukses dalam kegiatan selanjutnya. Usai ritual Tsifo Nopo para pekerja kebun membuat pagar (thel bahan) yang ditentukan dengan hati-hati posisinya oleh tobe dan maveva agar tidak menghalangi rute perjalanan yang dilalui roh-roh (Pah Tuaf). Jika terjadi kesalahan, maka malapetaka dapat terjadi, misalnya panen akan gagal. Konstruksi pagar harus kuat agar tidak dapat dilalui hewan peliharaan (babi dan sapi yang dilepas di hutan).
Kesibukan setelah ritual Tsifo Nopo terus berlanjut, khususnya pembuatan pagar yang kuat agar area kerja atau kebun yang digarap tidak mendapat gangguan dari hewan. Kesibukan berhenti ketika sudah muncul isyarat (takaf) alam berupa suara gemuruh (kelo atau ken neno) dan kicauan burung hujan (kol ulan) sebagai pertanda musim hujan sudah tiba(Foni, 2002).Tanda yang lain biasanya juga dari hadirnya kunang-kunang (ma’lafu) yang mengiringi datangnya senja. Ketika isyarat tersebut muncul, para pekerja kebun bergegas menyelesaikan pagar kebun mereka. Kehadiran isyarat-isyarat juga menjadi titik waktu mulainya pekerja kebun menyiapkan benih jagung dan benih padi (penfini-aenfini). Selain itu, masyarakat juga melakukan kegiatan turun ke kali dan mandi beramai-ramai (taikuf oe) sambil mencari udang dan belut untuk mempercepat datangnya hujan, seperti pernah terrekam di desa Kaenbaun (Foni, 2002).
Contoh pagar di kebun orang Timor tradisi di wilayah Tunbaba (Purbadi, 2010, p. 233)
4. Ritual memilih bibit (Tsimo Suan)
Ritual Tsimo Suan merupakan pekerjaan kaum perempuan (ibu) yang dilaksanakan berupa penanaman benih di kebun yang sudah disiapkan (Foni, 2002). Ritual dilaksanakan pada bulan November, selalu dipimpin oleh tobe dan maveva dan dilaksanakan di bale toko. Ritual memilih benih dimulai dengan kaum perempuan memilih benih di rumah masing-masing, kemudian benih tersebut dibawa dan didoakan di batu suci (fatu leu) dan tiang suci (ni ainaf) masing-masing rumah tangga (umebubu). Inti doa adalah memohon restu leluhur agar benih tumbuh baik dan menghasilkan panen melimpah. Setelah doa di rumah adat keluarga (umebubu) dilaksanakan, benih-benih tersebut dibawa ke gereja untuk didoakan secara Katolik, selanjutnya benih dibawa ke rumah adat masing-masing suku (umekanaf). Sebagai contoh, desa Kaenbaun dihuni oleh 8 suku dan memiliki 5 rumah suku serta satu gereja (Santo Yohanes Pemandi)(Purbadi, 2010), maka ritual benih skala suku dan desa dilakukan di 6 tempat-tempat penting tersebut. Fenomena yang sama juga terjadi di desa-desa lain di wilayah Tunbaba.
Puncak dari ritualTsimo Suan adalah doa adat di bale toko yang ada di kebun tobe, sama dengan tempat bagi upacara-upacara sebelumnya. Upacara di bale toko sama dengan upacara-upacara sebelumnya, dengan perlengkapan lilin, hewan korban, sopi, dan diakhiri dengan makan bersama (sae teke) semua peserta upacara. Setelah upacara doa¬†Tsimo Suan¬†selesai, para perempuan beramai-ramai menanam benih di kebun raja (naijuf) atau kebun tobe sebagai tanda penerimaan¬†Tsimo Suan¬†(Foni, 2002). Setelah penanaman di kebun raja atau tobe selesai, mereka kemudian menanam benih di kebun masing-masing diawali dengan doa sederhana (Onen Tjen, doa menanam). Proses menanam benih dimulai dari ‚Äúkaki kebun‚ÄĚ (lel‚Äôle haen) terletak di bagian rendah dan bertahap naik ke ‚Äúkepala kebun‚ÄĚ (lel‚Äôle Nakan) yang letaknya di bagian lahan yang relafif tinggi(Foni, 2002).
5. Ritual mendatangkan hujan (Toit Ulan)
Ritual¬†Toit Ulan¬†merupakan salah satu ritual penting terkait dengan hujan. Hujan di Timor tidak menentu datangnya, maka dengan ritual itu diyakini hujan dapat didatangkan sesuai kehendak manusia (Foni, 2002). Ritualnya sama dengan pada ritual sebelumnya, demikian juga tempatnya. Bedanya pada inti doa, yaitu memohon hadirnya hujan di lahan yang sudah disiapkan. Sebelum ritual dilakukan, tobe dan¬†maveva¬†berunding dengan warga desa untuk mencari penyebab belum datangnya hujan. Setelah penyebab ditemukan dan dilakukan denda serta ritual lain yang dikehendaki dunia arwah, maka ritual mendatangkan hujan dapat dilakukan. Doa ritual mendatangkan hujan ini sangat panjang, intinya merayu Tuhan dan memohon hujan dengan bahasa ‚Äútutur adat‚ÄĚ berupa puisi yang sangat indah (Foni, 2002).
Penyebab yang dicari umumnya dari pelaksanaan ritual sebelumnya, apakah ada kesalahan ritual, atau adanya kesalahan pada aspek yang lain, yang menyebabkan disharmoni dunia manusia dengan roh-roh dan arwah-arwah (Foni, 2002). Juga dicari, apakah ada hal-hal teknis di lapangan yang mengganggu kenyamanan maisokan dan roh-roh leluhur, atau ada perbuatan-perbuatan yang merusak bumi, seperti memotong akar secara salah, atau menggali tanah secara salah di tempat roh-roh berdiam. Jika sudah ditemukan penyebabnya, maka pelaku perbuatan dapat didenda uang (Foni, 2002), dan warga desa harus melakukan ritual di beberapa tempat untuk menghilangkan perbuatan salah tersebut.
6. Ritual membersihkan kebun (Tofa Lele)
Ritual Tofa Lele atau membersihkan lahan dilakukan beberapa pekan setelah menanam benih selesai dikerjakan, terutama ketika rumput dan gulma mulai bertumbuh di ladang. Pekerjaan pembersihan rumput dan gulma biasanya dilakukan secara individu maupun berkelompok karena orang Timor gemar bekerja bersama-sama. Jika pekerjaan dilakukan melibatkan banyak orang, maka ritualTofa Leledilaksanakan di bale toko seperti pola upacara sebelumnya. Bedanya pada inti doa, yaitu doa pengharapan agar dijauhkan dari berbagai malapetaka yang menghambat pertumbuhan tanaman.
Ritual¬†Tofa Lele¬†selalu diiringi dengan nyanyian¬†tofa rumput¬†(muistatili), dalam setiap syair lagu diawali dengan teriakan ‚Äúne‚ÄĚ oleh petani yang dituakan sebagai pemicu syair dan kemudian disambut oleh para pekerja yang lain(Foni, 2002). Syair-syair yang mereka nyanyikan terkait dengan tema membersihkan rumput dan gulma, serta bersifat membangkitkan semangat kerja. Suasana kerja kebun menjadi sangat ramai, akrab dan bersemangat. Suasana hingar-bingar sambil bekerja akhirnya menjurus pada olok-olok penyemangat agar pekerjaan segera selesai.
7. Ritual membendung aliran air (Eka Hoe)
Ritual Eka Hoe adalah ritual yang dilakukan pada awal musim hujan dan ditujukan untuk memohon keselamatan kebun dari bencana hujan (banjir, erosi, hilangnya kesuburan tanah), supaya tanaman tumbuh subur dan panen berhasil (Foni, 2002). Selain itu, upacara ini juga memohon agar tanaman dijauhkan dari segala hama (kepompong, belalang, burung, tikus, kera, babi, kambing) dan hama yang lain. Upacara ini biasanya dilakukan pada saat puncak musim hujan yang berlangsung selama satu minggu. Tobe dan maveva melakukan ritual di bale toko memohon leluhur agar panen memberi hasil yang berlimpah. Upacara ini biasanya juga dilakukan di berbagai tempat yang dianggap rawan, misalnya, pada pertemuan sungai dan tempat lain yang dianggap rawan.
8. Ritual memanen hasil pertanian (Ta’non)
Ritual Ta’non adalah ritual yang membahagiakan sebab warga desa akan mencicipi hasil kebun dan jerih payah mereka selama berbulan-bulan sebelumnya (Foni, 2002). Ritual Ta’non sangat istimewa sebab merupakan acara memohon ijin Tuhan, alam semesta dan leluhur untuk menuai dan menikmati hasil panenan yang ada di kebun. Hasil yang dipanen biasanya jagung umur pendek (pen saijan), ketimun, jewawut dan tanaman lainnya. Ritual Ta’non berarti mengatur agar boleh makan makanan baru (tah fe’o) dan hasil lain yang ditanam di kebun. Artinya, ritualTa’non merupakan ritual awal memetik hasil kebun, sebab jika ritual ini belum dilaksanakan maka berlaku larangan menikmati hasil kebun. Jika larangan dilanggar, maka malapetaka akan datang menjadi bencana.
Ritual Ta’non diawali dengan pengumuman warga desa agar mengandangkan semua ternaknya. Setelah ternak masuk kandang, dilakukan doa dan diikuti kegiatan membuang ketimun dan semangka serta percikan air pada hewan di dalam kandang. Makna kegiatan adalah mendatangkan kesuburan dan menghindarkan ternak dari bahaya merusak tanaman. Setelah selesai, para petani berjalan berkeliling kandang dan akan berkumpul kembali di depan kandang, sebagai simbol ternak pergi merumput dan tidak merusak tanaman. Ritual ini dipimpin oleh kepala suku dan dilaksanakan di rumah suku (umekanaf).
Dalam ritual ini kepala suku dibantu warga lain sebagai Meo (panglima perang), Meo Naek (panglima besar) dan Meo Ana (panglima kecil) melaksanakan rangkaian acara mengambil kayu dari hutan, memasak hasil panen perdana, dan melakukan makan bersama (sae teke). Upacara berlangsung sehari penuh, mulai dari rumah warga hingga berakhir di rumah suku (ume kanaf). Untuk jagung umur panjang, upacara dilakukan di batu suci suku (faut leudi rumah adat) dan mata air suci suku (oekana) di gunung, yang melibatkan seluruh warga suku (semua warga desa). Jika di desa Kaenbaun doa skala desa dilaksanakan di ume kanaf suku Basan (ada batu suci suku Basan sebagai suku pemimpin desa) terletak di tengah desa dan mata air suci suku Basan yang terletak di kaki bukit Kaenbaun (bnoko Kaenbaun)(Purbadi, 2010).
 
Contoh kandang babi di Timor (desa Kaenbaun) (Purbadi, 2010, p. 239)
9. Ritual menjaga hama burung (Tiut Kolo)
Ritual Tiut Kolo atau ritual menjaga hama burung ini dilakukan pada saat tanaman pertanian (padi) mulai berisi hingga padi mulai menguning, dan dilakukan di bale toko seperti ritual yang lain. Ritual ini dimaksudkan untuk mengawali kegiatan menghalau burung agar tidak memakan bulir padi yang berisi (Foni, 2002). Selain itu juga untuk mengusir hama yang lain, misalnya, kera, babi, sapi dan kambing serta ternak yang lain. Para laki-laki biasanya bertugas menjaga malam hari, sedang para perempuan, biasanya para gadis (feotnai munif) bertugas pada siang hari, namun pada saat ini dilakukan siapapun yang menyediakan waktunya, bahkan termasuk para lanjut usia. Para penjaga biasanya menggunakan tali panjang yang digantungi kain berwarna-warni (hone) sepanjang kebun, kemudian digerak-gerakkan dari tempat yang tinggi (teut kolo) setiap kali burung datang.
Pada waktu menjaga kebun inilah, dilantunkan nyanyian atau pantun muda-mudi yang menambah meriah suasana di kebun. Sambil bernyanyi mereka mempererat keakraban, disertai dengan kegiatan membakar jagung umur panjang (pena tnais). Dalam suasana meriah penuh lagu dan pantun serta membakar jagung, para muda-mudi berkesempatan saling mendekati dan menyampaikan perasaan cinta mereka. Memang menjadi kebiasaan, para muda-mudi Tunbaba mengungkapkan cinta mereka di kebun-kebun jagung atau di alam bebas, dan mereka menuliskan nama gabungan (pasangan) di pohon kayu putih (Foni, 2002).
10. Ritual menghalau hujan (Tkau Ulan)
Ritual Tkau Ulan adalah ritual adat yang ditujukan untuk menghalau curah hujan yang datang terlampau tinggi sepanjang musim hujan dan mengakibatkan kerusakan tanaman pertanian yang sedang tumbuh di kebun, terutama padi dan jagung (Foni, 2002). Ritual ini biasanya dilakukan menjelang musim panen, dimaksudkan agar hujan yang berlebihan dapat berkurang dan sinar matahari bertambah untuk mematangkan hasil tanaman. Ritual ini penting sebab hasil tanaman sangat diharapkan melimpah dan siap digunakan dalam setahun. Ritual ini biasanya dipimpin oleh tua-tua adat dan dilaksanakan di tempat yang tinggi atau di tempat suci desa (faotkana-oekana) dengan menggunakan hewan korban berbulu putih sebagai simbol menghalau awan hujan dan diharapkan muncul awan putih dan sinar matahari(Foni, 2002).
11. Ritual panen padi (Houn Ane)
RitualHoun Ane terkait dengan kegiatan memanen padi yang sudah masak. Ritual dilakukan secara individu di rumah dan di kebun masing-masing keluarga, dengan inti doa adalah memberitahu leluhur sebagai pemilik dan penjaga kebun tentang kegiatan memanen padi yang akan dilakukan(Foni, 2002). Kegiatan Houn Ane selalu dalam suasana tenang untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan agar roh padi berkenan bersemayam di kebun, sebab suasana ramai akan membuat roh padi pergi dari kebun. Doa di kebun dilakukan di tempat yang disebut kika atau tempat sementara untuk meletakkan padi hasil tuaian sebelum dibawa ke sane. Doa di sika cukup dengan sirih-pinang dan sopi. Doa juga memohon agar para pemanen padi mendapat perlindungan dan menghasilkan panen berlimpah.
Kegiatan memanen padi umumnya dilakukan beberapa hari dan dipimpin oleh pihak keluarga yang penting (atoin amaf), biasanya anak laki-laki pertama (Purbadi, 2010) yang mewakili pemilik kebun (abeut). Kegiatan panen hanya boleh dilakukan pada siang hari. Para pemanen akan berhenti ketika kicauan burung koa (koak) terdengar, sebagai pertanda pekerjaan panen hari itu dihentikan dan pemanen segera pulang ke rumah (kampung). Jika pekerjaan belum selesai, pihak pemilik kebun akan mengikatkan tanda tertentu sebagai pembatas dan pengikat roh padi agar tetap tinggal dan kegiatan memanen dapat dilanjutkan esok hari.
12. Ritual memilih bulir padi (Hail Ane)
Ritual Hail Ane merupakan lanjutan dari ritual Houn Ane, yaitu terkait dengan kegiatan memilih bulir padi sebagai kegiatan pasca-panen, dilakukan para perempuan secara bersama-sama (rombongan) melepaskan bulir-bulir padi dari tangkainya dengan cara menginjak-injaknya (Foni, 2002). Pihak yang berperan aktif memimpin kegiatan ini adalah atoin amaf (saudara laki-laki dari ibu keluarga). Selama kegiatan hail ane, atoin amaf duduk di dekat mesbah (nabeukane) sebagai simbol penjaga roh padi. Upacara dilakukan di mesbah dengan menggunakan sirih-pinang dan dua botol sopi, dengan inti doa agar roh padi bersemayam dalam tumpukan padi dan tetap hadir hingga selesai kegiatan hail ane tersebut.
Setelah ritual dilaksanakan, kemudian para wanita menginjak-injak tumpukan padi, selanjutnya batang-batang padi dipisahkan dari butir-butir padi dan dikumpulkan agar segera dapat dijemur dan disimpan ke dalam lumbung (lopo) bagian atas. Butir-butir padi dimasukkan ke dalam karung (kalo) atau bakul (bo’o) dan bakul besar (ka’ut). Setelah selesai dilakukan pengukuran hasil panen dengan menggunakan ukuran jumlah kalo (karung 50 Kg atau 100 Kg) atau menggunakan ukuran jumlah blek (14 Kg). Hasil yang diperoleh biasanya dibandingkan dengan hasil dari musim tanam sebelumnya, untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya.
13. Ritual panen jagung (Seke Pena)
RitualSeke Pena (panen jagung) terkait dengan kegiatan memanen jagung umur panjang (penapnais) dan agak berbeda dengan ritual yang lain (Foni, 2002). Maklum, jagung adalah tanaman yang istimewa di kalangan orang Tunbaba, khususnya di Kaenbaun (Purbadi, 2010). Doa bersama dilakukan di bale toko, selanjutnya dilakukan panen jagung umur panjang yang ada di sekitar bale toko. Setelah selesai ritual, selanjutnya, para pekerja memanen di kebun masing-masing. Sebelumnya, atoin amaf setiap keluarga akan menentukan tempat para-para yang akan digunakan untuk meletakkan mesbah jagung (pele pena).
Seik pena¬†atau¬†seke pena¬†dilakukan dengan suasana riang gembira, diawali dengan pengambilan beberapa batang jagung bersama bulirnya, kemudian diikatkan pada tiang di tengah pondok jagung (pele), dan disertai dengan doa adat. Proses memanen jagung dimulai dari ‚Äúkaki kebun‚ÄĚ (lele haen) secara bertahap menuju ‚Äúkepala kebun‚ÄĚ (lele nakan). Proses ini persis sama dengan pada saat menanam benihnya, sebab ada keyakinan bahwa kekuatan gaib setiap kebun ada pada bagian kepala kebun (lele nakan).
Lopokhas Kaenbaun ini adalah simbol laki-laki dan selalu digunakan untuk menyimpan padi (Purbadi, 2010, p. 311)
14. Ritual mengikat jagung (Kaibu Pena)
Ritual Kaibu Pena (mengikat jagung) merupakan rangkaian dari ritualseke pena (panen jagung). Setelah jagung dipanen, jagung diletakkan di pele (mesbah jagung), selanjutnya dilakukan kegiatan mengikat jagung (kaibu pena). Atoin Amaf akan menunggui kegiatan mengikat jagung ini dengan cara duduk di mesbah jagung sambil minum sopi, sampai kegiatan selesai. Ritual Kaibu Pena diawali dengan doa adat di mesbah jagung dengan persembahan hewan korban, disertai sirih-pinang, lilin, dan sopi. Ritual dipimpin oleh atoin amaf, inti doa adalah agar jagung dapat berkumpul dengan baik.
Kegiatan mengikat jagung akan berlangsung semalam suntuk diselingi dengan minum sopi, sirih pinang, dan suguhan jagung goreng. Para pekerja biasanya menyanyikan lagu nyanyian mengikat jagung (oebainit), yang menghormati Liurai Sonbai (penguasa lokal masa lalu yang terkenal) dan para arwah leluhur. Mitosnya, Liurai Sonbai sebagai asal mula datangnya padi dan jagung di Timor. Liurai Sonbai dan para raja (usif) yaitu Uis Ukat dan Uis Sakunab diyakini sebagai pendiri kerajaan Tunbaba. Pada akhir kegiatan dilakukan penghitungan hasil panen dengan ukuran aisaf (10 aisaf = 60 bulir jagung), atau kabutu (3 kabutu = 180 bulir jagung). Hasil panen yang melimpah menambah harum desa penghasilnya.
15. Ritual mengundang roh makanan ke kampung (Nau Balaif)
Ritual Nau Balaif berkaitan dengan kegiatan membersihkan kebun dari tumpukan kulit jagung yang ada di sekitar tempat mengikat jagung (kaibu pena) sebagai tempat berdiam roh makanan (Foni, 2002). Biasanya, meskipun proses membawa jagung berbeda-beda diantara para petani, namun mereka meletakkan satu aisaf jagung diikatkan pada tiang utama pondok petani di kebun mereka sebagai tanda menunggu pelaksanaan ritual Nau Balaif yang akan dilaksanakan bersama. Ritual Nau Balaif hakekatnya adalah ritual yang mengajak roh jagung di kebun pulang ke kampung. Doa ritual Nau Balaif dilakukan oleh tobe di bale toko, intinya mengucapkan terima kasih kepada arwah leluhur untuk hasil panen yang telah diperoleh, serta ajakan roh jagung pulang ke kampung dan bersemayam di rumah keluarga di Tunbaba.
16. Ritual menyimpan hasil panen (Tahik Mnahat)
Setelah hasil panen jagung tiba di kampung (kompleks hunian warga desa), jagung dirapikan dan disusun dalam rumah bulat (umebubu) (Foni, 2002; Purbadi, 2010). Jagung-jagung dalam ikatan rapi diletakkan di atas para-para melingkar di atas lantai rumah bulat, susunannya indah sehingga menciptakan wujud plafond rumah bulat. Jagung yang disusun di rumah bulat ini berada di atas tungku tiga batu, sehingga diawetkan secara alamiah oleh asap tungku yang digunakan untuk memasak setiap hari. Jagung yang digunakan sebagai benih diletakkan tepat di atas tungku api umebubu agar tetap awet karena menerima asap pertama. Jagung yang dikonsumsi diambil dari jagung tepi lingkaran dan bergerak ke tengah secara melingkar. Ritual Tahik Mnahat adalah ritual di dalam rumah bulat (umebubu), intinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan arwah leluhur yang telah memberikan panen melimpah, juga mohon perlindungan agar jagung yang sudah disimpan di rumah bulat bebas dari hama tikus maupun bubuk (fufuk), atau yang lain(Foni, 2002).
Rumah bulat (umebubu) simbol perempuan, digunakan untuk menyimpan jagung di Timor (desa Kaenbaun) (Purbadi, 2010, p. 256)
Jagung tertata rapi di dalam umebubu menjadi struktur plafond yang indah di desa Kaenbaun (Purbadi, 2010, p. 260)
17. Ritual menempatkan kembali roh makanan dalam rumah (Seve So’e)
Ritual Seve So’e dilakukan setelah semua rangkaian kegiatan penuaian hasil pertanian (terutama padi dan jagung) selesai dikerjakan dan telah tiba di dalam rumah (Foni, 2002). Secara harafiah, ritual Seve So’e berarti pelepasan batang padi dan jagung pada tiang utama rumah adat (ni ainaf) sesaat sebelum upacara panen dan mengambil makanan. Ritual ini bertujuan mengundang dan menjamu roh makanan agar bersemayam dalam rumah keluarga sampai musim tanam yang akan datang. Ritual juga bertujuan agar keluarga pemilik panenan dijauhkan dari sikap boros dan menjunjung sifat hemat dalam menggunakan hasil pangan (so’e), sehingga persediaan pangan tercukupi sampai musim tanam berikutnya.
Ritual Seve So’e diisi dengan makan bersama menikmati hasil perkebunan yang telah diperoleh dengan hidangan nasi (padi baru dipetik), jagung (baru dipetik), umbian, kelapa, tebu, pisang dan yang lain (Foni, 2002). Makanan dicampur dengan tatanan tertentu, kemudian diedarkan kepada semua peserta ritual untuk disantap bersama. Acara makan bersama diawali dengan doa yang dipimpin oleh warga tertua disertai ajakan untuk makan sekenyang-kenyangnya. Ritual ini dulu dipraktekkan secara luas di Tunbaba, tetapi sekarang hanya ada di Bokon.
Jagung disimpan di dalam umebubu sekitar tiang suci (ni ainaf) dan batu suci (fautleu) di sebuah rumah bulat di desa Kaenbaun (Purbadi, 2010, p. 259)
18. Ritual persembahan hasil panen kepada Uis Pah (Tatam Pen Tauf).
Ritual¬†Tatam Pen Tauf¬†adalah ritual terakhir dari rangkaian ritual pertanian di wilayah Tunbaba (Foni, 2002) sebagai ritual yang intinya adalah pemberian upeti kepada kepala suku pemimpin desa dengan istilah ‚Äúpenyerahan jagung upeti‚ÄĚ (Purbadi, 2010). Setelah semua kegiatan panen selesai, warga dan suku menyampaikan terima kasih kepada raja atau usif setempat, dengan cara menyerahkan sebagian hasil panennya berupa jagung terpilih dan padi terpilih (pena pupun ane pupun). Penyerahan ‚Äúupeti‚ÄĚ tersebut merupakan wujud nyata terima kasih kepada¬†usif¬†atau¬†naijuf¬†setempat (raja lokal) yang dianggap sebagai wakil leluhur yang memberi kekuatan dan kesuburan (Foni, 2002). Penerima ‚Äúupeti‚ÄĚ ini di desa Kaenbaun adalah kepala suku Basan yang dianggap suku pemimpin dan pendiri desa (Purbadi, 2010; Foni, 2002).
Jagung upeti milik Martinus Taus dan David Foni berupa jagung terpilih yang diikat rapi dan indah khas desa Kaenbaun (Purbadi, 2010, p. 374)
PENUTUP
Ritual-ritual yang dipaparkan dalam tulisan ini menjelaskan adanya hubungan erat antara orang Tunbaba dengan dunia arwah leluhur mereka (be’i nai), dunia arwah-arwah lain (maisokan), dan Tuhan (Uis Neno). Kegiatan pertanian bagi mereka bersifat relijius (suci), sebab melibatkan secara hati-hati dan cermat partisipasi sesama manusia (atoni), nenek moyang (be’i nai), arwah-arwah lain (maisokan), dan Tuhan (Uis Neno) sebagai pemilik kehidupan. Padi dan jagung terbukti merupakan tanaman utama dan penting di wilayah Tunbaba dan mendapat penghormatan secara khusus dalam rangkaian ritual yang ada dalam siklus pertanian.
PUSTAKA
- Foni, W. (2002). Budaya Pertanian Atoni Pah Meto: Suatu Studi Siklus Ritual Kegiatan Pertanian Lahan Kering Atoni Pah Meto Tunbaba di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Tesis (tidak diterbitkan), Salatiga: Program Studi Magister Studi Pembangunan, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Purbadi, Y. D. (2010). Tata Suku dan Tata Spasial pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan di Desa Kaenbaun di Pulau Timor. Disertasi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Eksistensi Pura Mekah Sebagai Harmonisasi Hindu - Islam di Banjar Binoh, Desa Ubung, Denpasar - Bali
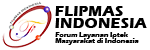
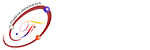





Komentar Via Website :0 Komentar